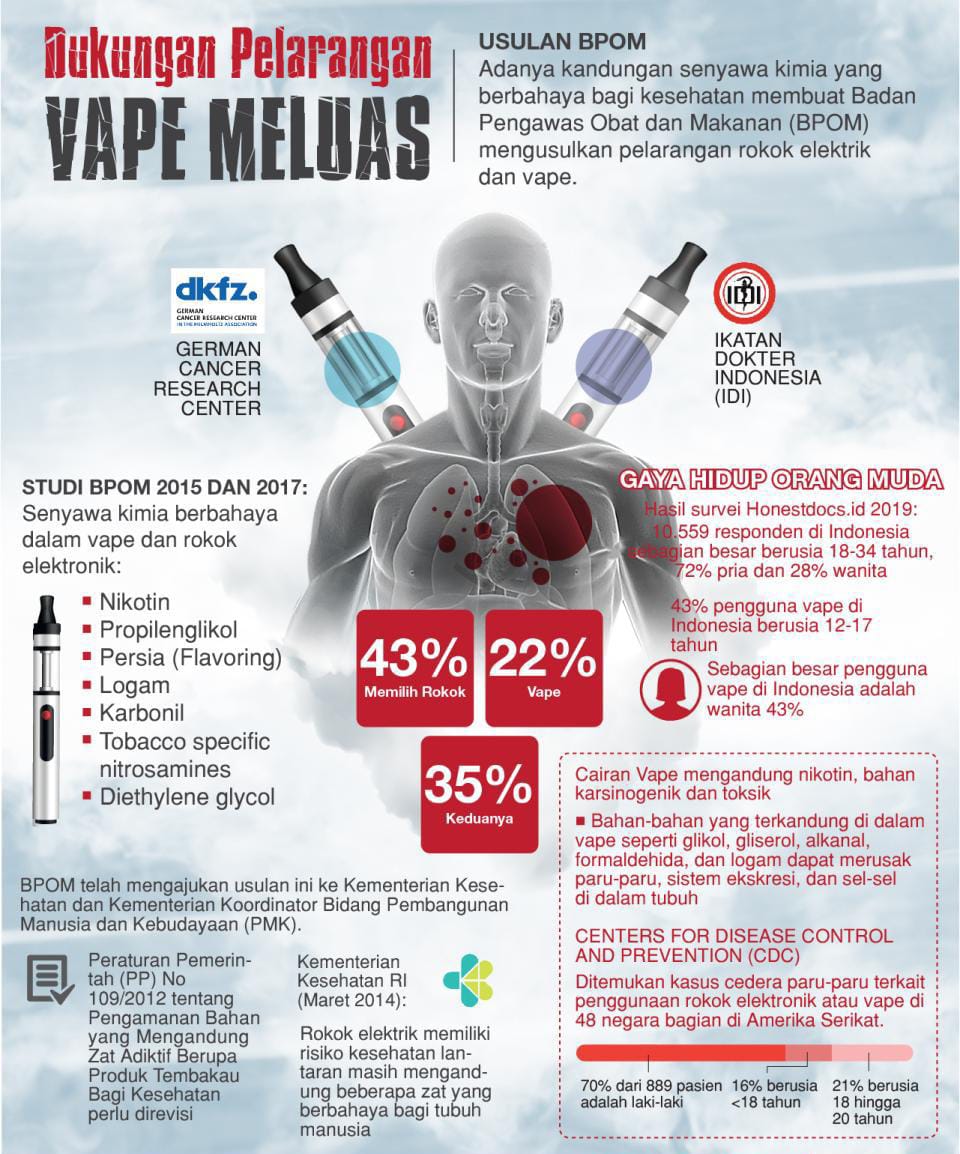Aceh | Sudutpenanews.com : Setiap tanggal 10 Oktober, dunia memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesehatan mental bagi seluruh lapisan masyarakat. Tahun ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengangkat tema “Mental Health in Humanitarian Emergencies”, yang menyoroti dampak krisis kemanusiaan terhadap kesejahteraan psikologis individu dan komunitas.
Di tengah berbagai bencana alam, konflik sosial, dan ketidakpastian ekonomi yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia, kesehatan jiwa menjadi isu yang semakin mendesak. Luka psikologis sering kali tidak tampak, namun dampaknya bisa jauh lebih dalam dan berkepanjangan. Sayangnya, banyak dari luka tersebut dibiarkan diam, tersembunyi di balik senyum dan rutinitas.
Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sekitar 6% penduduk Indonesia mengalami gangguan mental emosional, dan prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia mencapai 7 per 1000 rumah tangga. Data ini kemungkinan besar meningkat pasca pandemi COVID-19 dan berbagai bencana yang terjadi dalam lima tahun terakhir.
Sementara itu, Asian Journal of Psychiatry (2021) mencatat bahwa Indonesia memiliki rasio psikiater hanya sekitar 0,3 per 100.000 penduduk—jauh di bawah standar WHO yang merekomendasikan minimal 1 psikiater per 10.000 penduduk. Ketimpangan ini menyebabkan banyak individu dengan gangguan mental tidak mendapatkan penanganan yang memadai.
Luka yang Tak Terlihat: Dari Anak Hingga Lansia
Kesehatan jiwa bukan hanya isu orang dewasa. Anak-anak dan remaja menghadapi tekanan psikologis yang semakin kompleks, mulai dari konflik keluarga, tekanan akademik, hingga dampak sosial media. UNICEF Indonesia (2022) melaporkan bahwa satu dari tiga remaja menunjukkan gejala depresi, namun hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan profesional.
Sementara itu, kelompok lanjut usia sering kali mengalami kesepian, kehilangan makna hidup, dan penurunan fungsi sosial. Dalam buku The Psychology of Aging (Whitbourne, 2016), dijelaskan bahwa keterlibatan sosial dan dukungan emosional memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan mental lansia. Ketika lansia merasa terhubung dan dihargai, risiko gangguan mental seperti depresi dapat ditekan secara signifikan.
Stigma yang Membungkam: Mengapa Banyak yang Takut Mencari Bantuan?
Salah satu hambatan terbesar dalam penanganan kesehatan jiwa adalah stigma. Di masyarakat Indonesia, gangguan mental masih sering dikaitkan dengan label negatif seperti “kurang iman”, “lemah mental”, “tidak waras”, atau bahkan “kerasukan”. Pandangan ini membuat banyak orang enggan mencari bantuan profesional karena takut dianggap gila, dikucilkan, atau mempermalukan keluarga.
Andrew Solomon, dalam bukunya The Noonday Demon: An Atlas of Depression (edisi revisi 2017), menulis, “Depresi bukanlah tanda kelemahan, tetapi hasil dari pertarungan yang terlalu lama.” Kutipan ini menggambarkan bahwa penderita gangguan mental bukanlah individu yang lemah, melainkan pejuang yang tengah berjuang melawan badai dalam dirinya.
Studi oleh Corrigan et al. (2016) dalam Psychological Science in the Public Interest menunjukkan bahwa stigma publik dan stigma internal (self-stigma) secara signifikan menghambat individu untuk mencari bantuan profesional. Semakin tinggi stigma yang dirasakan, semakin rendah kemungkinan seseorang untuk mengakses layanan kesehatan jiwa.
Menemukan Ruang Aman: Peran Individu dan Lingkungan Sosial
Di luar sistem dan kebijakan, ada kekuatan yang sering kali lebih dekat dan berdampak langsung terhadap kesehatan jiwa seseorang: lingkungan sosial. Keluarga, teman, rekan kerja, dan komunitas memiliki peran penting dalam menciptakan ruang aman bagi individu yang sedang berjuang secara mental.
Ruang aman bukanlah tempat fisik semata, melainkan suasana yang memungkinkan seseorang merasa diterima, didengar, dan tidak dihakimi. Dalam buku Lost Connections karya Johann Hari (2018), dijelaskan bahwa salah satu akar dari depresi adalah hilangnya keterhubungan—baik dengan orang lain, dengan makna hidup, maupun dengan diri sendiri. Maka, membangun koneksi yang tulus dan suportif menjadi langkah awal yang sangat penting.
Kita tidak perlu menjadi psikolog untuk membantu orang lain. Mendengarkan dengan empati, menghindari komentar yang meremehkan, dan menawarkan kehadiran yang konsisten sering kali jauh lebih berarti daripada nasihat yang panjang. Studi oleh Segrin & Passalacqua (2017) dalam Journal of Social and Clinical Psychology menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki efek protektif terhadap stres dan gejala depresi, terutama pada kelompok usia muda dan dewasa awal.
Mengubah Narasi: Dari Diam Menjadi Bicara
Salah satu langkah paling transformatif dalam isu kesehatan jiwa adalah mengubah narasi dari diam menjadi bicara. Ketika seseorang berani mengungkapkan perasaannya, ia sedang membuka pintu bagi pemulihan. Ketika masyarakat mulai berbicara tentang kesehatan mental secara terbuka, stigma perlahan akan terkikis.
Dalam konteks budaya Indonesia yang cenderung menekankan ketahanan dan kerahasiaan, membuka diri tentang kondisi mental sering kali dianggap tabu. Namun, generasi muda mulai menunjukkan perubahan. Munculnya komunitas diskusi, konten edukatif di media sosial, dan kampanye kesadaran menjadi bukti bahwa suara-suara tentang kesehatan jiwa semakin terdengar.
Kita perlu mendukung gerakan ini dengan cara yang sederhana namun bermakna: tidak menghakimi, tidak menyederhanakan penderitaan orang lain, dan tidak memaksakan solusi. Seperti yang ditulis oleh Brené Brown dalam bukunya Dare to Lead (2018), “Empati tidak pernah dimulai dengan ‘setidaknya’. Empati dimulai dengan mendengarkan dan hadir.”
Penutup: Jangan Diamkan Luka di Dalam
Hari Kesehatan Jiwa Sedunia bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan pengingat bahwa luka di dalam diri tidak boleh terus disembunyikan. Luka psikologis yang tidak terlihat bukan berarti tidak nyata. Ia bisa tumbuh, membebani, dan mengikis kualitas hidup seseorang jika tidak ditangani dengan tepat.
Merawat jiwa adalah tindakan berani. Mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja adalah langkah pertama menuju pemulihan. Dan menjadi pendengar yang baik bagi orang lain adalah bentuk kepedulian yang bisa menyelamatkan nyawa.
Di tengah dunia yang penuh tekanan dan ketidakpastian, mari kita ciptakan ruang yang lebih manusiawi—di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di hati kita sendiri. Karena setiap orang berhak merasa aman, didengar, dan dicintai. Jangan diamkan luka di dalam. Mari bicara, mari peduli, mari pulih bersama.
Oleh : dr. Rezki Muttaqin
Referensi:
Kementerian Kesehatan RI. (2018). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).
UNICEF Indonesia. (2022). Mental Health Status of Adolescents in Indonesia.
Winoto, Y., & Zakiyyah, Z. (2023). Tren Penelitian Kesehatan Mental di Era Digital. Jurnal Kesehatan dan Informasi.
Media Penerbit Indonesia. (2022). Kesehatan Mental: Pemahaman, Pencegahan, dan Pengobatan.
Corrigan, P. W., et al. (2016). The Impact of Mental Illness Stigma on Seeking and Participating in Mental Health Care. Psychological Science in the Public Interest, 15(2), 37–70.
Hari, J. (2018). Lost Connections. Bloomsbury Publishing.
Brown, B. (2018). Dare to Lead. Random House.
Segrin, C., & Passalacqua, S. A. (2017). Social Support and Mental Health in Emerging Adults. Journal of Social and Clinical Psychology, 36(5), 419–439.
WHO. (2023). Mental Health in Humanitarian Emergencies: Policy Brief.
Whitbourne, S. (2016). The Psychology of Aging. Wiley.